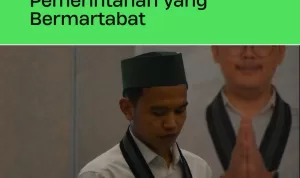Oleh: Holil Aksan Umarzen
Pengamat Budaya dan Ketua Forkodetada (Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah) Jawa Barat
Dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi partisipatif, rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya pandai membangun citra, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang substantif, sistematis, dan berkelanjutan. Di tengah populernya figur Dedi Mulyadi—yang dikenal luas dengan pendekatan “nyunda” dan citra merakyat—perlu kiranya dilakukan peninjauan kritis terhadap sejumlah pendekatan kepemimpinan beliau, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan budaya.
1. Kebijakan Spontan yang Minim Kajian dan Tindak Lanjut
Dedi Mulyadi dikenal dengan gaya kepemimpinan spontan dan responsif. Namun, banyak kebijakan yang diambil tampak bersifat reaktif dan tidak berbasis kajian akademik atau kajian dampak jangka panjang. Contohnya, perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih dinilai sejumlah akademisi hanya sebagai simbolisme tanpa perbaikan sistem layanan publik. Hal ini menunjukkan bagaimana aspek branding lebih dikedepankan ketimbang transformasi substansi.
2. Modifikasi Budaya tanpa Menyentuh Esensi Sunda
Dedi sering memodifikasi simbol budaya Sunda menjadi bagian dari pencitraannya—baik melalui pakaian, narasi konten, maupun ritual panggung. Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah substansi nilai-nilai Sunda seperti kearifan lokal, musyawarah, kesantunan, dan welas asih benar-benar diwujudkan dalam kebijakan publik? Ataukah budaya hanya dijadikan aksesori visual yang menutupi kekosongan kebijakan?
3. Pencampuran Ritual Budaya dan Syariat Agama
Dalam berbagai konten yang ditampilkan ke publik, tampak adanya percampuran antara praktik budaya Sunda dengan simbol-simbol agama, seolah-olah keyakinan leluhur identik dengan syariat. Meski upaya pelestarian budaya patut dihargai, pencampuran ini bisa membingungkan masyarakat awam dan menimbulkan bias keyakinan. Hal ini membuka ruang bagi glorifikasi masa lalu tanpa kejelasan nilai spiritual yang dibangun secara transenden.
4. Pencitraan Berlebihan: Emosi Publik di Atas Substansi Kebijakan
Citra Dedi sebagai “bapak aing” dibangun melalui konten viral di media sosial: memberi makan orang kecil, menyuapi tukang becak, menangis bersama masyarakat desa. Namun sayangnya, konten ini seringkali hanya menggugah emosi tanpa disertai transparansi kebijakan yang sistematis, program yang terukur, atau visi pembangunan daerah yang jelas.
5. Fokus pada Simbolisme, Bukan Perbaikan Layanan
Penggantian nama rumah sakit, pemugaran gerbang tradisi, atau pemasangan ornamen nyunda memang menarik secara visual, namun tidak menyentuh akar persoalan seperti antrean panjang layanan publik, birokrasi yang lamban, hingga inefisiensi anggaran. Akademisi dari UPI pernah mengkritik bahwa kebijakan seperti ini lebih sibuk mengurus “kulit luar” daripada “isi dalam”.
6. Diskriminasi Kultural Terselubung
Kebijakan yang terlalu menonjolkan budaya Sunda tanpa ruang dialog untuk kebudayaan lain bisa menciptakan eksklusivitas terselubung. Hal ini berisiko menyingkirkan kelompok non-Sunda dari proses pembangunan sosial dan politik daerah. Kepemimpinan inklusif seharusnya merangkul semua identitas dengan proporsional dan adil.
7. Militerisasi Remaja: Disiplin atau Dominasi?
Wacana membangun “barak militer” untuk membina kedisiplinan remaja menuai kritik keras dari para pemikir kebebasan sipil. Rocky Gerung misalnya menyebut pendekatan itu sebagai bentuk kediktatoran budaya baru. Remaja tidak hanya butuh disiplin, tapi juga perlu ruang berpikir kritis, pendidikan moral, dan kesempatan berpartisipasi dalam wacana demokratis.
8. Kebijakan Pendidikan Tergesa
Kebijakan pembukaan kuota sekolah negeri secara besar-besaran tampak populis, namun menyebabkan dampak serius pada sekolah swasta. Banyak sekolah swasta yang kehilangan siswa hingga mengalami ancaman tutup. Kebijakan yang tidak dikaji secara menyeluruh hanya akan menambah daftar masalah sosial pendidikan.
Rakyat Butuh Pemimpin yang Berpikir Sistemik
Pemimpin ideal bukan hanya piawai membangun narasi emosional, tetapi mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan publik berbasis data, berorientasi hasil, inklusif, dan berkelanjutan. Figur seperti Dedi Mulyadi memiliki magnet publik yang kuat, namun magnet itu perlu diarahkan untuk menarik rakyat menuju kemajuan, bukan hanya menghibur mereka di ruang digital.
Kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat adalah yang membumi secara budaya, religius secara akhlak, cerdas secara visi, dan kuat dalam sistem. Tanpa itu semua, kita hanya akan terjebak dalam teatrikal kekuasaan yang meriah di luar, tetapi kosong di dalam. [**]